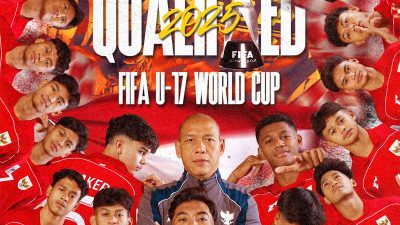Jakarta (Riaunews.com) – Pemerintah rezim Joko Widodo dihujani protes terkait draf Omnibus Law Cipta Kerja yang menyebut bahwa Undang-undang (UU) bisa diubah menggunakan Peraturan Pemerintah (PP).
Namun kemudian Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dengan mudahnya menyudahi polemik tersebut.
Menteri yang merupakan kader PDIP dan sarat kontroversi sejak mencuatnya kasus Harun Masiku ini angkat bicara, dengan menyebut hanya persoalan teknis: salah ketik.
Klausul yang diklaim salah ketik itu tertulis dalam Pasal 170 dengan tiga ayat di dalamnya. Adapun isi pasal tersebut berbunyi;
(1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) berdasarkan Undang-undang ini pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-undang yang tidak diubah dalam Undang-undang ini.
(2) Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(3) Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah pusat dapat berkonsultasi dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PusaKo) Universitas Andalas Padang, Feri Amsari mengaku sulit menerima alasan salah ketik yang melibatkan tiga ayat dalam satu pasal tersebut.
“Typo (salah ketik) tidak wajar karena terlalu panjang. Sebagai begawan hukum tata negara termasuk kita semua terkejut dengan isi itu. Saya rasa pemerintah tidak punya alasan lain selain typo,” kata Feri kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/2/2020).
Feri menilai bahwa ada intensi lain di balik salah ketik itu. Menurut Feri, kekuasaan yang diserahkan kepada pemerintah untuk membuat UU sangat berbahaya. Menurutnya, kekuasaan mengubah UU di Presiden akan menghasilkan sistem yang absolute serta otoriter.
“Semangatnya orde baru sekali, kita bisa kembali ke zaman dulu yang pemerintah buat kebijakan dan DPR hanya tukang stempel,” jelas dia.
Mestinya, kata dia, UU itu hadir untuk memastikan peraturan di bawahnya mengikuti dan berkesesuaian dengan peraturan tertinggi. Sehingga pada kasus ini, tegas dia, tidak mungkin PP bisa menjadi acuan dari pembentukan UU.
“Itu betul-betul meletakkan pemerintahan kekuasaan absolute. Bahkan itu bisa otoriter,” jelas dia.
Feri mengingatkan bahwa Kemenko Polhukam masih memiliki waktu untuk mengubah hal tersebut. Mahfud MD, kata dia, adalah orang yang berkompeten mengenai peraturan perundangan di Indonesia.
Senada, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai tidak masuk akal jika ada salah ketik dalam draf Omnibus Law. Menurutnya pihak yang menyusun draf tersebut bukan orang sembarangan yang latah salah ketik.
“Typo itu dari O jadi I itu kan typo. Tapi kalau satu pasal itu, ada dua kemungkinan entah dia ada yang bikin enggak ngerti hukum atau sengaja,” kata Bivitri kepada CNNIndonesia.com.
Bivitri pun menyindir bahwa hierarki perundangan-undangan yang menyebutkan UU lebih tinggi daripada PP adalah makanan umum orang hukum. Sehingga ia mengatakan pilihan kesengajaan adalah paling mungkin dalam hal tersebut.
“Karena soal UU yang tidak bisa digantikan PP itu anak fakultas hukum semester 1 juga sudah belajar,” kata dia.
Bivtri menambahkan, menarik kewenangan UU di bawah Presiden sama saja mengubah kekuasaan menjadi sentralistik. Adapun pihak yang paling diuntungkan dalam hal ini adalah pemerintah, dan yang paling dirugikan adalah masyarakat.
Bivitri mengambil contoh pemerintahan Orde Baru yang kekuasaan cenderung ke pemerintah.
“Karena power-nya yang sangat besar, bisa jadi akan muncul kroni di sekitaran presiden seperti waktu Orba. Dulu kan begitu karena kekuasaan kuat muncul banyak yang dekat dengan presiden yang punya kekuasaan. Ini berbahaya,” jelas dia.
Imbas lain, masyarakat tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan kebijakan. Pemerintahan juga akan lebih tertutup. Menurut Bivitri ini akan menyebabkan pengawasan terhadap pemerintah semakin kecil.***