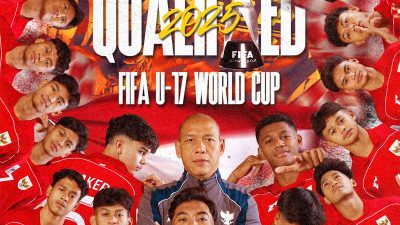Jakarta (Riaunews.com) – Pernyataan Presiden Joko Widodo dan pihak Istana yang meminta masyarakat menyampaikan kritik keras demi perbaikan layanan publik diharapkan diikuti dengan kebijakan nyata. Tanpa kebijakan nyata, pernyataan Jokowi dinilai cuma pepesan kosong.
Kebijakan nyata itu misalnya, dengan moratorium atau penangguhan penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE).
Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SafeNet), Damar Juniarto mengatakan moratorium atau penangguhan penggunaan UU ITE merupakan langkah konkret Jokowi untuk membuktikan pernyataannya. Seruan ini, kata dia, bisa didorong oleh Komnas HAM.
“Menarik kalau dihidupkan wacana untuk memoratorium UU ITE. Jadi tanpa itu sih nganggepnya kayak, ya imbauan kosong,” kata Damar kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/2/2021).
Selain itu, langkah moratorium juga bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). Menurut dia, MA misalnya dapat mengeluarkan surat edaran agar lembaga peradilan tak menindaklanjuti kasus lewat UU Nomor 11 Tahun 2008 tersebut.
Damar mengingatkan Jokowi maupun pemerintah agar tak perlu khawatir terkait kritik dan masukan dari masyarakat. Menurut dia, pemerintah mestinya lebih khawatir soal iklim kebebasan masyarakat sipil dalam berekspresi.
Mengutip laporan koalisi masyarakat sipil misalnya, dia menyebut tingkat hukuman lewat UU ITE mencapai 96,8 persen. Dari jumlah itu, 88 persen pelakunya dimasukkan ke penjara.
“Jadi mungkin itu salah satu yang menjadi aspek penyebab orang mengatakan bahwa UU ITE itu momok kalau mau menyampaikan kritik di media sosial,” katanya.
Sementara itu, Aktivis Dandhy Dwi Laksono mengatakan pernyataan Jokowi itu tak pernah terwujud dalam sebuah kebijakan. Lagipula, kata dia, dalam beberapa kasus, orang-orang yang mengkritik pemerintah tidak pernah didengar.
“Dan ya tidak terjewantahkan dalam kebijakan,” kata Dandhy kepada CNNIndonesia TV, Rabu (10/2) malam.
Jokowi punya lingkaran sendiri
Dandhy mencontohkan dua kasus besar yang terjadi dalam setahun terakhir. Pertama, masukan masyarakat terhadap penanganan pandemi. Sejak awal, masyarakat sipil, akademisi, epidemiolog, dan media telah memberikan tekanan yang sangat kuat di media sosial. Pemerintah, kata Dandhy, baru mengumpulkan epidemiolog belakangan, ketika menyadari kasus positif Covid sudah tembus satu juta.
Kasus kedua, kata dia, adalah kasus penolakan terhadap Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Publik, menurut Dandhy telah mengkritisi undang-undang yang dinilai bermasalah secara prosedural ini tanpa kekerasan. Hal itu mereka lakukan melalui mimbar akademik, artikel di media massa, hingga akhirnya di jalanan.
Akan tetapi, pemerintah tidak memberikan respons yang pantas. Menurutnya, usul dari masyarakat tidak menjadi bagian dalam proses pengambilan keputusan.
“Ada dunia sendiri, ada logika sendiri, ada circle sendiri yang menjadi bagian dari pengambilan keputusan,” ungkap jurnalis Ekspedisi Indonesia Biru tersebut.
Dandhy sendiri pernah ditangkap polisi karena cuitannya di twitter tentang Papua pada 26 September 2019. Ia dituduh melanggar Pasal 28 ayat (2), jo Pasal 45 A ayat (2) UU No.8 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 14 dan Pasal 15 No.1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana.***