
Itulah yang terjadi usai Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyatakan keberatannya ke pihak Universitas Indonesia (UI) pada pada Kamis (7/11) lalu, akibat namanya dicatut dalam disertasi Bahlil Lahadalia. Bahlil adalah petinggi partai Golkar yang juga Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral).
Bahlil meraih gelar doktor pada program Studi Doktor Kajian Stratejik Global (SKSG) di Universitas Indonesia (UI) sekitar sebulan lalu. Dia memperoleh predikat cumlaude atas disertasinya berjudul ‘Kebijakan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia’.
Dalam disertasi itu disebutkan jika informan utamanya adalah JATAM. Namun, JATAM menolak klaim itu. Sebab faktanya tak pernah ada dan konsen wawancara langsung dari Bahlil. Melainkan, ada salah satu peneliti yang diduga jadi joki atas disertasi Bahlil.
Pernyataan JATAM itu, ramai di media sosial (utamanya X) selama sepekan ini. Publik pun memperbincangkan, termasuk kalangan civitas akademika dan guru besar UI.
Sulistyowati Irianto, Guru Besar Universitas Indonesia (UI), keras mengkritik kampusnya atas gelar akademik yang sempat diberikan kepada Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu.
Tak cuma soal validitas datanya yang bermasalah dan melanggar etika, dia juga menyoroti soal prosedural formal. Gelar akademik itu dinilainya cacat secara hukum. Yaitu soal aturan program doktor yang ditempuh minimal 4 semester (24 bulan). Sedangkan, Bahlil bisa melenggang meski masa studinya hanya 20 bulan.
“Ini cacat secara hukum,” ujar Sulistyowati kepada Konde.co, Selasa (12/11).
Dia juga menyesalkan, secara sengaja civitas akademika UI termasuk promotor diduga ada yang juga terlibat memasukkan artikel dari disertasi Bahlil ke jurnal yang diketahui predator. Padahal, itu semestinya tidak bisa dilakukan karena termasuk academic misconduct.
“Ada nilai etika moral yang memaksa orang-orang terlibat mengundurkan diri sebagai rasa tanggung jawab, atau dipaksa mengundurkan diri. Di universitas seperti di Jerman ada Ombudsman,” katanya.
Meskipun sudah ada indikasi bermasalah, dia menyayangkan sikap UI kala itu, yang justru memberikan jadwal ujian doktor. Bahkan, hasil ujiannya cumlaude.
Padahal dari kajian kelas lintas fakultas dan strata yang Ia ikuti soal disertasi Bahlil, kualitasnya rendah dengan substansi dan metodologi bermasalah. Disertasi Bahlil juga tak berimbang mengangkat sisi masyarakat terdampak kebijakan seperti perempuan dan marginal.
“Halo UI, berhentilah menyakiti diri dan kehormatanmu sendiri. Sebagai civitas akademika UI, kami menuntut pemulihan kehormatan UI,” ujar Sulistyowati Irianto.
Usai ramai jadi bahasan publik, pada Rabu (14/11) kemarin, pihak UI akhirnya mengeluarkan siaran resmi soal penangguhan kelulusan Program Doktor (S3) Bahlil. Ini mengikuti peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022, selanjutnya akan mengikuti sidang etik. Selain itu, Dewan Guru Besar UI juga akan melakukan sidang etik terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan dalam proses pembimbingan mahasiswa S3 di SKSG.
“Langkah ini diambil untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan di UI dilakukan secara profesional dan bebas dari potensi konflik kepentingan,” tulis Ketua Majelis Wali Amanat (MWA UI), Yahya Cholil Staquf.
Konde.co kemudian menghubungi JATAM soal respons terbaru UI ini. Usai sepekan sejak surat keberatan yang mereka layangkan tak ada tanggapan dari pihak UI.
Dini Pramita dari JATAM mengatakan pihaknya mengapresiasi sikap UI atas permohonan maaf UI kepada publik. Namun, JATAM melihat ini hanya sebagai formalitas untuk menanggapi kegaduhan publik.
“Kami mendorong UI bisa melakukan investigasi mendalam dan menyeluruh terhadap kasus ini dan berikan sanksi tegas kepada seluruh pihak yang terlibat pada kecurangan dan pelanggaran etik dalam disertasi Bahlil,” kata Dini Pramita kepada Konde.co, Rabu (13/11).
Sampai kasus tersebut diselesaikan secara tuntas, JATAM juga memutuskan tidak melayani seluruh permintaan wawancara dari mahasiswa atau peneliti UI.
“Sampai kasus ini diselesaikan secara baik dan tegas oleh UI,” katanya.
‘Obral’ Gelar Akademik: Praktik Tak Etis, Mencoreng Integritas
Dosen Senior Ilmu Politik dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (PUSKAPOL) UI, Hurriyah, turut angkat bicara.
Dia menilai, persoalan perguruan tinggi di Indonesia hari ini termasuk cenderung mudah memberikan ‘obral’ gelar akademik ke para politisi. Kepentingannya bisa beragam hal yang bersifat material sampai politis.
“Ini adalah praktik tidak etis perguruan tinggi, mencoreng reputasi, integritas, kredibilitas institusi akademik,” kata Hurriyah kepada Konde.co, Rabu (13/11).
Ini konteksnya bukan saja gelar akademik yang diperoleh dengan ‘jalur instan’. Seperti pada kasus disertasi Bahlil yang dugaannya menggunakan joki dan melanggar etika akademik. Namun juga pada gelar akademik seperti Honoris Causa.
Gelar akademik, menurutnya adalah pengakuan formal yang semestinya diberikan kepada mereka yang punya kontribusi akademik nyata. Dia mencontohkan gelar Doktor Honoris Causa yang layak diberikan kepada Miriam Budiardjo, yang memang bekerja sebagai akademisi yang punya rekam jejak bagus, panjang dan jasanya yang besar dalam ilmu politik.
Sebaliknya, gelar akademik Honoris Causa bukan ‘diobral’ tiba-tiba pada seseorang yang nihil kontribusi akademik. Apalagi, jika kepentingannya hanya agar namanya ‘menjual’ untuk kontestasi atau saat terjun di politik.
Kaitannya dengan ini, artis Raffi Ahmad juga pernah ramai diperbincangkan karena tiba-tiba mendapatkan gelar akademik Doktor Honoris Causa dari sebuah perguruan tinggi luar negeri, yang ternyata tak diakui oleh Kemendikbud. Bahkan, banyak yang menilai kampusnya tidak kredibel. Tak lama usai mendapat gelar akademik itu, Raffi pun masuk kabinet Presiden saat ini.
“Ini memang juga ada ‘penyakit’ di masyarakat dimana orang tergila-gila dengan gelar. Bukan hanya akademik. Politisi kalau mau maju atau jadi pejabat, itu semua gelar muncul,” katanya.
Itu disebabkan oleh adanya persepsi bahwa gelar akademik itu bisa memberikan legitimasi, pengakuan, prestise.
“Ini kan sesuatu yang salah kaprah,” ucap nya.
Sementara sebagai pemberi ‘obral’ gelar akademik, kampus pun bisa meraih keuntungan. Misalnya untuk menaikkan segmen pasar, popularitas, sampai pragmatis ingin dapat keuntungan seperti akses/jejaring.
“Anggapan cara mengambil legitimasi ya harus punya gelar. Tapi masalahnya, gak mau menempuh proses. Di sini ketemulah, pragmatisme perguruan tinggi dan kemalasan para politisi,” katanya.
Lalu, apa dampaknya kualitas pejabat yang menjadi pengejar ‘obral’ gelar jabatan ini?
Sulistyowati dengan tegas menjawab “pejabat dengan tingkat integritas rendah, tidak akan bisa diharapkan bikin kebijakan yang berpihak kepada rakyat, termasuk di dalamnya perempuan dan kelompok marjinal”.
Ini senada dengan Hurriyah yang menyatakan bahwa politisi yang menempuh cara-cara tidak etis untuk mendapatkan sesuatu termasuk gelar akademik, maka menurutnya, tak ada yang bisa diharapkan dari kualitasnya dalam menghasilkan produk kebijakan. Utamanya, yang berpihak pada masyarakat termasuk terhadap perempuan dan marginal. Sebab orientasinya sebatas gelar akademik yang mendatangkan keuntungan pribadi.
“Kalau orang tidak malu menempuh cara-cara tidak etis, sulit bagi kita mengharapkan kebijakan politik yang etis,” pungkasnya.
This article first appeared on Konde.co and is republished here under a Creative Commons license.
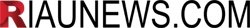 Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga











