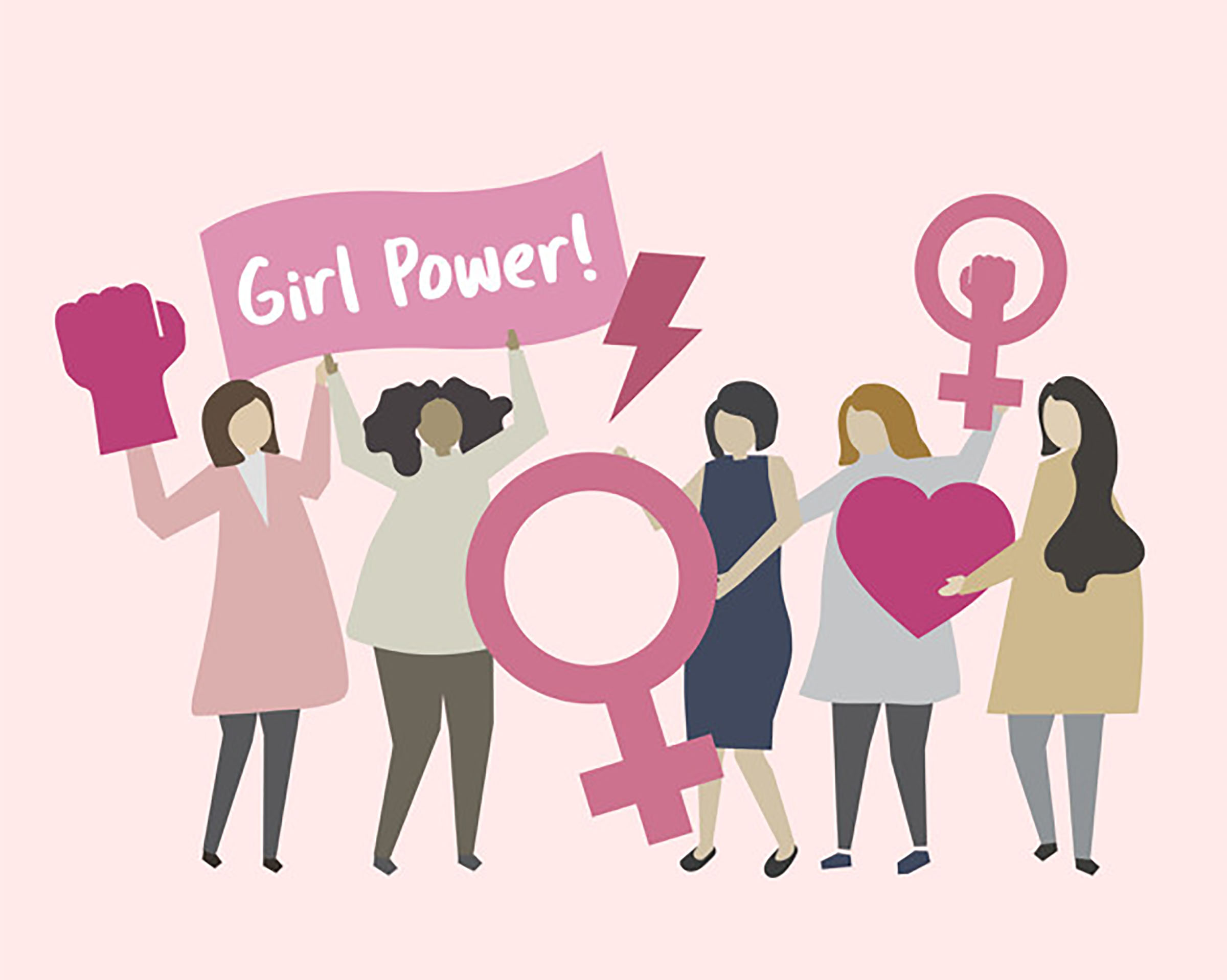
Oleh Hesti Nur Laili, S.Psi
Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Lenny N. Rosalin dalam keterangannya menyebutkan bahwa selama periode tahun 2023 indeks pemberdayaan perempuan semakin meningkat.
Menurutnya, semakin berdaya seorang perempuan, maka akan makin mampu memberikan sumbangsih pendapatan signifikan bagi keluarga, menduduki posisi strategis di tempat kerja, dan terlibat dalam politik pembangunan dengan meningkatnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. (Republika.co.id, 6/1/2024).
Hal tersebut dibuktikan dengan makin banyaknya perempuan menjadi seorang pemimpin, baik di tingkat desa sebagai kepala desa, lalu tingkat daerah sebagai pemimpin daerah, hingga menduduki posisi-posisi strategis sebagai pejabat negara, termasuk salah satunya pemimpin di Kementerian dan lembaga.
Oleh karenanya, KemenPPPA menargetkan peningkatan atas indeks pembangunan gender ini untuk meningkatkan peran dan kualitas perempuan dalam pembangunan di tahun 2024 berbasis kesetaraan gender. (Antaranews.com, 6/1/2024).
Meningkatnya indeks pemberdayaan perempuan tersebut, memunculkan sebuah pertanyaan besar, yakni benarkah meningkatnya indeks pemberdayaan perempuan tersebut selaras dengan meningkatnya kualitas hidup perempuan?
Apakah Pemberdayaan Perempuan Sejalan dengan Kualitas Hidup Perempuan?
Posisi dan jabatan penting di ruang publik maupun politik yang berhasil diduduki oleh perempuan seolah menjadi tolok ukur keberhasilan pemberdayaan perempuan. Ironisnya, dibalik keberhasilan tersebut ternyata tidak memiliki korelasi terhadap maraknya kasus KDRT, tingginya angka perceraian, meningkatnya kasus kekerasan dan pelecehan seksual, juga maraknya kasus bunuh diri.
Pada kasus perceraian saja, menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) di sepanjang tahun 2022, terdapat 516.334 kasus perceraian di Indonesia yang telah diputus oleh pengadilan. 75% dari kasus tersebut merupakan kasus gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri. (Databoks.katadata.co.id, 2/11/2023).
Sementara untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di rentang tahun 2022 mencapai 5.526 kasus. Di rentang tahun 2023, kasus KDRT yang dilaporkan kepada KemenPPPA 75% dari angka rata-rata itu adalah KDRT dengan jenis kekerasan fisik. (Medcom.id, 9/12/2023).
Kemudian KemenPPPA juga mencatat laporan kasus kekerasan yang dialami perempuan per Januari hingga 29 Mei 2023 adalah sebanyak 8.615 kasus, dengan kategori: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi, trafficking, dan kasus penelantaran. (Metrotvnews.com, 4/6/2023).
Kasus-kasus di atas belum termasuk dengan maraknya kasus bunuh diri. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa meningkatnya indeks pemberdayaan perempuan sangat tidak sejalan dengan banyaknya dan makin meningkatnya kasus-kasus tersebut.
Sedangkan parameter indeks pemberdayaan perempuan dikatakan meningkat jika dinilai dari sisi kapitalisme semata. Seorang perempuan dikatakan sukses ketika ia bisa keluar dan mampu mengekspresikan dirinya dengan maksimal, mengeksplorasi segala kemampuan yang dimiliki, bahkan bebas menjadi apapun yang mereka inginkan, termasuk menang dalam persaingan dengan kaum lelaki.
Padahal jika ditelaah dengan teliti, keluarnya perempuan dari rumah untuk ikut serta dalam mencari nafkah, meniti karir dan menjabat di suatu lembaga atau politik, tidak memberikan perubahan apapun kecuali menambah masalah dari sisi perempuan itu sendiri.
Misalnya saja dalam hal bekerja, perubahan ekonomi tidak serta merta menjadi lebih baik ketika seorang istri ikut serta mencari nafkah. Karena pada hakikatnya, distribusi kekayaan yang tidak merata dan banyak menumpuk di kalangan kapitalis lah yang membuat ekonomi suatu negara itu timpang. Bukan dikarenakan sang istri yg tidak ikut serta mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Itulah tugas negara dalam mengatur agar bisa menyejahterahkan rakyatnya, bukan malah membuat para istri dan ibu untuk keluar rumah dan ikut bekerja. Yang pada akhirnya bukan solusi yang didapatkan dari masalah kekurangan ekonomi yang menghimpitnya, tetapi justru masalah baru akan timbul dari keluarnya perempuan untuk ikut andil dalam mencari nafkah.
Anak-anak menjadi terlantar karena kesibukan ibunya. Akibat keterlantaran itu, banyak anak menjadi bermasalah saat mereka bersosialisasi di tengah masyarakat hanya untuk mencari perhatian karena kurangnya perhatian di dalam rumah. Istilah “broken home” menjadi marak sejak para ibu turut menyingsingkan lengan dalam mencari sesuap nasi.
Apakah masalahnya cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Ketika perempuan mengalami kelelahan akibat kesibukannya turut mencari nafkah, maka anak-anak seolah dituntut menjadi dewasa sejak dini untuk memahami kelelahan yang dialami orangtuanya. Alhasil tak hanya kurangnya perhatian dalam pengasuhan yang mereka alami, tetapi juga luka batin akibat perilaku-perilaku buruk yang tanpa sadar dilakukan oleh seorang ibu ketika berhadapan dengan anaknya yang dianggapnya sulit diatur.
Kelelahan dan tekanan kerja bertemu dengan keadaan anak yang tidak sesuai dengan ekspektasi (misalnya tidak mau makan, tidak mau bereskan mainan, dll), tentu menimbulkan emosi amarah yang meletup yang pada akhirnya menorehkan luka batin yang dalam bagi sang anak.
Sekali lagi, apakah cukup sampai di situ masalahnya? Jawabannya tidak. Masalah yang tidak ditangani dengan tepat tentu akan menimbulkan masalah lain. Luka batin yang dialami banyak anak, ketika dewasa kemungkinan besar akan menjadi sosok yang takut untuk menikah dan takut untuk memiliki anak.
Tidak bisa dipungkiri bahwa anak yang lahir dan tumbuh di lingkungan broken home cenderung memiliki masalah psikologis serius. Itu belum ditambah jika orang tuanya bercerai.
Bekerjanya seorang perempuan di tengah kemelut rumah tangga yang dihadapi, menjadi problem besar tersendiri. Satu sisi ia harus berupaya menafkahi anak, di sisi lain harus mendidik dan mengasuh seorang diri. Yang pada akhirnya lagi-lagi memicu masalah lain seperti anak yang makin tidak terurus, emosi yang kian tidak stabil, depresi bahkan bunuh diri.
Feminisme Jadi Bumerang Sendiri bagi Perempuan
Bahkan dalam kasus KDRT saja, keluarnya perempuan untuk bekerja atau memiliki jabatan tinggi di sebuah perusahaan tidak lantas menghentikan kasus tersebut. Tidak sedikit bahkan para istri meregang nyawa di tangan suami meski telah berhasil menghasilkan uang sendiri.
Itu belum ditambah dengan faham kesetaraan yang mereka agungkan untuk menjadi bebas, termasuk bebas dalam berpakaian. Betapa banyak kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual di tempat kerja maupun publik terjadi lantaran pelaku tidak tahan melihat kemolekan tubuh perempuan berbusana minim? Lagi-lagi, apakah meningkatnya indeks pemberdayaan perempuan tersebut dapat menghentikan tingginya kasus tersebut?
Nyatanya pemberdayaan perempuan berbasis feminisme yang diagungkan dan dianggap solusi agar tidak tertindas oleh kaum laki-laki sedikitpun tidak memberikan dampak dalam menanggulangi kasus-kasus di atas, dan tidak pula memberikan jaminan keamanan serta kenyamanan bagi perempuan itu sendiri.
Karena sejatinya adanya kasus KDRT bukan karena faktor istri tidak pandai menghasilkan uang sehingga dipandang sebelah mata. Termasuk juga kasus-kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual yang terjadi bukan karena perempuan dianggap makhluk lemah, tetapi lantaran dampak dari gaya hidup bebas, maraknya pornografi, normalisasi pacaran dan zina, hingga aborsi, yang pada akhirnya merusak generasi dari segala lini.
Seringnya keberadaan kasus-kasus di atas banyak beranggapan bahwa penyebabnya adalah budaya patriarki. Padahal menyalahkan budaya itu seutuhnya tidaklah tepat. Karena berbagai persoalan perempuan justru muncul sejak sistem kapitalisme sekulerisme diterapkan.
Narasi-narasi kesetaraan gender digaungkan, seolah akar masalah dari perceraian, KDRT, pelecehan dan pemerkosaan yang terjadi pada wanita karena ketimpangan gender alias budaya patriarki dan hanya bisa diselesaikan jika kesetaraan gender diterapkan demi menyelamatkan para perempuan dari diskriminasi dan penindasan.
Sayangnya ide kesetaraan gender tersebut justru menjadi bumerang tersendiri bagi para perempuan. Istilah lainnya “masalahnya apa, solusinya apa” tidak nyambung.
Tingginya angka depresi turut menyumbang efek dari meningkatnya indeks pemberdayaan perempuan itu sendiri. Karena lagi-lagi menurut pandangan kapitalisme, perempuan dikatakan berdaya dan sukses ketika ia mandiri secara ekonomi.
Berbeda dengan pandangan islam, meningkatnya indeks pemberdayaan perempuan bukan dilihat dari sisi ekonomi, tetapi bagaimana ia mampu menjadi istri sholihah taat suami dan mampu mencetak generasi unggul di bawah pengasuhannya.
Bila dalam pandangan kapitalisme, keberadaan perempuan di rumah untuk mengasuh anak merupakan bentuk diskriminasi, eksploitasi, bahkan penjajahan terhadap perempuan, namun justru islam melihat bahwa sosok perempuan wajib dimuliakan dan dihormati. Salah satu wujud kemuliaan pada perempuan adalah membiarkan mereka di rumah dan mengambil peranan penting untuk mencetak generasi unggul.
Perannya di rumah sebagai pengasuh anak bukanlah peran receh yang dipandang sebelah mata dan tak berdampak apa-apa, justru sebaliknya memiliki dampak sangat besar untuk mencetak generasi unggul di masa depan.
Islam telah menempatkan segala sesuatunya sesuai fitrahnya. Perempuan dengan segala sifat kelemah-lembutannya diberdayakan sebagai pabrik pembentuk peradaban, sedangkan laki-laki diberikan peran sebagai pencari nafkah bukan untuk menunjukkan kekuatannya melebihi perempuan, tetapi sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab yang diberikan Allah SWT.
Di sisi lain, negara juga turut andil dalam menyejahterahkan rakyatnya yang di dalamnya terdiri atas jaminan kebutuhan pokok sandang, pangan, papan, layanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, serta kemudahan bagi para lelaki untuk mencari nafkah dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang luas maupun memberikan modal bantuan usaha serta membekali mereka dengan ketrampilan untuk bekal bekerja.
Kemudian, selain pemberdayaan perempuan di rumah sebagai pengasuh dan pencetak generasi, di dalam islam, perempuan juga diberdayakan di sektor pendidikan dan kesehatan tanpa harus dipecah fokusnya dengan nominal gaji yang ingin didapatkan.
Negara telah mencukupi dan memenuhi segala kebutuhan guru dan tenaga kesehatan tanpa harus mencampur-adukkan dengan berapa jumlah pasien, jumlah murid, atau berapa jam waktu bekerja yang telah mereka jalani.
Selain itu, negara juga tegas dalam menegakkan hukum. Sistem islam memberlakukan efek jera bagi pelanggaran syariat, termasuk di dalamnya jika seorang suami memandang rendah dan memperlakukan tidak baik istrinya seperti KDRT.
Mencegah masuknya tontonan bersifat pornografi, mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan sehingga meminimalir adanya aktivitas pacaran maupun terjadinya pelecehan seksual. Dalam hal ini negara juga secara tegas memberikan hukuman bagi para pelanggar-pelanggar tersebut dengan hukuman berat yang memiliki efek jera bagi pelaku maupun orang lain yang belum melakukannya.
Dari paparan di atas harusnya kita lebih bijak menjadikan tolak ukur keberhasilan perempuan, dari sudut pandang islam atau sudut pandang lain yang tidak selaras antara fakta dan faktor pengukur keberhasilan. *
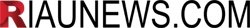 Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga











